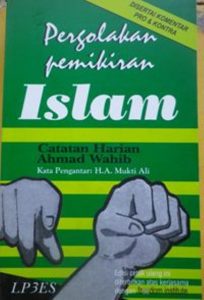
Prawacana: Wahib dan Ibrahim
DALAM beberapa hal Ahmad Wahib mirip dengan Ibrahim. Keduanya pernah melakukan suatu pergulatan pemikiran yang berbahaya dan menyiksa. Ibrahim gelisah, mencari Tuhan, dan ia mengendarai akal untuk menuju ke sana; Wahib gelisah, mencari Tuhan, dan ia pun memakai akal. Ibrahim menyusuri jejak-jejak Tuhan lewat fenomena alam semesta; Wahib menjajakinya lewat filsafat dan fisika. Ibrahim memulai pencariannya dari titik nol; Wahib pun mencoba menge-nol-kan dirinya.
Namun hasil yang dicapai keduanya berbeda, meski tidak berlawanan. Ibrahim sampai pada tujuan ketika ia masih hidup, saat ia, menurut riwayat, sudah berumur ratusan tahun. Inilah satu pencapaian yang boleh disebut sebagai penemuan terbesar umat manusia, mengalahkan penemuan-penemuan dalam bidang lainnya sejak awal peradaban hingga sekarang. (Ibrahim menemukan Tuhan! Mana ada penemuan lain yang lebih hebat daripada ini?) Ibrahim pun lalu diangkat menjadi nabi, disebabkan kegelisahan dan usaha pencariannya yang tak kenal lelah telah membuat Tuhan, mungkin, terharu. Gelar ini mengantarkannya sebagai bapak moyang dari agama-agama besar dunia.
Kepada Wahib, Tuhan memberikan waktu yang terlalu singkat untuk berproses. Dari usianya yang 31 tahun, secara efektif hanya 8 tahun terakhir yang digunakannya untuk berpikir serius dan radikal tentang Tuhan, sampai akhirnya Wahib bertemu dengan Tuhan – dalam arti yang sebenar-benarnya – saat melangkahkan kaki keluar dari kantor majalah Tempo. Sebelum itu Tuhan hanya hidup dalam pikiran dan angan-angan Wahib. Ia dipanggil Tuhan begitu cepat, dan sejarah tak pernah mencatat apakah ia bahagia dengan panggilan itu atau malah protes. Statusnya sebagai “manusia biasa” tak memungkinkannya berbuat seperti Ibrahim, yang konon sempat protes kepada Izrail ketika rohnya hendak dicabut: “Bagaimana mungkin sang Kekasih tega mematikan kekasihNya?” Tentu saja Izrail bingung sebab selama karirnya sebagai malaikat maut tak pernah ada yang bertanya begitu. Dilaporkannya hal itu kepada Tuhan, yang lalu menitipkan jawaban: “Apakah sang Kekasih tidak rindu pada kekasihNya?” Wahib, jangankan sempat bertanya, tentu tak sempat pula menyangka bahwa dirinya akan mati pada saat itu. Tragis.
Dalam usahanya mencari Tuhan, tidak seperti Ibrahim, sebetulnya Wahib tidak benar-benar mulai dari nol. Ia hanya sempat berusaha mundur ke titik itu. Dalam hukum akumulasi pengetahuan, Wahib barangkali seperti Newton, yang kebetulan berdiri di pundak para jenius terdahulu. Para jenius itu adalah nabi-nabi, orang-orang suci, filsuf, dan pemikir jenis lain. (Muhammad pun hanya meneruskan “penemuan-penemuan” para nabi sebelumnya). Wahib tumbuh dan besar dalam lingkungan yang kuat kebertuhanannya. Ia hidup di masa ketika segala macam pengetahuan telah terbangun dengan rapi di antara bermacam simbol dan tumpukan buku-buku, sementara Ibrahim hidup dan berjuang pada saat pengetahuan manusia masih berada pada tahap-tahap permulaan, tanpa ada kertas dan sistem simbol untuk mengabadikan penemuannya. Karena itu jalan yang dilalui Ibrahim jauh lebih curam dan berliku daripada Wahib. Jika ia terperosok, tak ada manusia yang bisa menolong. Untung ia berhasil. Namun, perbedaan masa hidup itu pulalah yang akhirnya memungkinkan Ibrahim mendapat wahyu dan diangkat sebagai nabi. Sedangkan Wahib, setua apa pun usianya dan sekeras apa pun usahanya, tak akan mungkin menyamai derajat pendahulunya itu. Namun jika masalahnya adalah masa hidup, boleh jadi jika Wahib hidup pada masa kenabian (formal) belum ditutup, kegelisahan dan pencariannya yang juga tak kenal lelah itu akan membuat Tuhan mempercayakan dirinya sebagai nabi.
Tuhan Ada vs Tuhan Tidak Ada
Tuhan manakah yang ditemui Wahib sekeluarnya dari kantor Tempo itu? Samakah dengan Tuhan yang ketika hidup selalu dicarinya dan tak henti menggelisahkan pikirannya? Entah. Kita tak pernah tahu dengan pasti sebab kita telah kehilangan kontak dengan Wahib. Ahli jelangkung barangkali bisa menghubungkan Wahib dengan kita. Tapi Wahib tentu tak mau bicara, sebab cara yang digunakan untuk menghubunginya termasuk perbuatan syirik yang dibenci ayahnya, dan tentu pula tidak disukainya.
Meskipun Wahib sendiri belum final merumuskan pemikiran teologisnya, dari catatan hariannya dapatlah kita mengidentifikasi Tuhan “seperti apa” yang dicari Wahib. Sebelumnya perlu dicatat bahwa Wahib tidak pernah memaksakan diri untuk harus bertuhan, atau untuk mengakui bahwa Tuhan harus ada. Baginya, ada atau tidak ada Tuhan, keduanya mempunyai hak yang sama untuk dipikirkan. Keduanya mempunyai kemungkinan yang sejajar dalam kesalahan dan kebenarannya. Jika dalam pencariannya tersimpulkan bahwa Tuhan ada, itulah yang dianut. Tetapi jika diperoleh kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada, mau bagaimana lagi. Itulah resiko mencari: ketemu atau tidak ketemu. Menurut Wahib: “Sesungguhnya, bagaimana orang disuruh dengan sukarela untuk percaya pada Tuhan ada, kalau tidak boleh memikirkan kemungkinan benarnya “kepercayaan” bahwa Tuhan tidak ada.” (PPI, hal. 47).
Jadi kedua-duanya, kemungkinan Tuhan ada dan Tuhan tidak ada, mesti dipikirkan dalam porsi yang sama. Yang diinginkan Wahib sebenarnya adalah kepercayaan akan adanya (atau tidak adanya) Tuhan dengan dilandasi kesadaran, pemikiran, kejujuran, dan keikhlasan. Seseorang percaya Tuhan bukan karena keterpaksaan, bukan karena ayah dan ibu orang beriman, bukan karena masyarakat mengharuskan demikian, bukan karena aturan pemerintah, dan sebagainya. Pun ia tidak bertuhan bukan karena teman-temannya ateis, bukan karena ia komunis, bukan karena undang-undang negara, dan lain sebagainya.
Pandangan ini memang berisiko tinggi. Taruhannya adalah keselamatan di kehidupan nanti. Kita tidak pernah tahu secara mutlak manakah yang lebih benar, Tuhan ada atau Tuhan tidak ada. Namun kita yakin di antara keduanya pasti hanya satu yang benar. Tidak mungkin benar dua-duanya atau salah dua-duanya. Pun tak mungkin ada alternatif ketiga. Para filsuf dan pemikir telah sejak lama menyadari resiko ini, dan mereka sadar bahwa mereka harus memilih. Namun pilihan apa pun yang diambil harus dengan kesadaran sendiri, disertai penalaran yang kuat dan rasional. Kita tidak pernah menjumpai seorang filsuf menerima atau menolak Tuhan tanpa dasar argumentasi. Rata-rata filsuf idealisme seperti Plato, Plotinus, dan Descartes menerima keberadaan Tuhan, dan pemikiran yang dibangun dalam filsafat tersebut memang mengakui adanya satu idea tertinggi yang bisa diidentikkan dengan Tuhan. Semua filsuf skolastik adalah orang-orang beragama, karena menurut mereka agama (wahyu) yang notabene berasal dari Tuhan tidak bertentangan dengan akal. Sementara di pihak lain, Darwin menafikan adanya Tuhan, dan teori evolusinya memang tidak menyisakan sehelai ruang pun bagi Tuhan. Marx menolak Tuhan, dan teori kelasnya berusaha keras menyingkirkan agama yang dianggap sebagai candu itu dari kehidupan masyarakat. Nietzsche menyatakan kematian Tuhan, dan lewat filsafatnya ia menciptakan uber-man, manusia unggul, untuk menggantikan kedudukan Tuhan. Sigmund Freud meniadakan Tuhan, dan dengan ketekunan yang mengherankan ia membangun grand theory yang menyatakan bahwa Tuhan yang selama ini diagungkan umat manusia sebenarnya hanyalah ilusi, pengganti figur Ayah. Sartre memilih tidak mempercayai Tuhan, dan ajaran eksistensialismenya yang rumit itu memang telah menyingkirkan Tuhan sejak premis pertama.
Namun memilih mempercayai Tuhan pun tidak lantas berarti menyelesaikan masalah. Ada banyak teori, ajaran, atau kepercayaan tentang Tuhan. Namun lagi-lagi yang pasti benar hanya satu. Mengutip NDP HMI, dalam bab 1 (Dasar-dasar Kepercayaan) disebutkan sebuah postulat yang menyatakan, jika ada banyak kepercayaan, maka kemungkinan yang tersedia hanya dua: kesemuanya salah atau salah satu saja di antaranya yang benar. Menganut kepercayaan yang salah atau dengan cara yang salah, bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya.
Ada beragam kepercayaan di dunia ini. Masing-masing mempunyai dasar dan bentuk teologis yang berbeda. Secara garis besar pandangan yang mempercayai adanya Tuhan terbagi menjadi dua: politeisme (paham banyak Tuhan) dan monoteisme (paham satu Tuhan). Kedua isme ini pun masih terbagi-bagi lagi ke dalam banyak agama dan sistem kepercayaan. Begitu seterusnya. Bahkan ketika kita sudah memilih satu agama saja pun, yang monoteis, Islam misalnya, tetap masih akan dibingungkan oleh bervariasinya aliran teologi yang berkembang. Dan, sekali lagi, yang benar hanya satu. Atau malah salah semuanya.
Berpikir sebagai Proses
Nah, di antara banyak ragam kepercayaan itu, bagaimana kita dapat memastikan pilihan? Wahib menulis: “Pada hemat saya, orang-orang yang berpikir itu, walaupun hasilnya salah, masih jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah salah karena tidak pernah berpikir.” (PPI, hal. 23). Yang penting bagi Wahib adalah proses berpikirnya, bukan hasilnya. Orang yang berpikir adalah orang yang berani menanggung akibat dari hasil pikirannya. Ketika seseorang berpikir, baginya ada dua kemungkinan: benar dan atau salah. Namun selama ia masih bisa dan terus berpikir, salah satu dari dua kemungkinan itu sebenarnya belum dicapainya secara penuh. Ia masih akan berubah. Sedangkan orang yang tidak berpikir tidak akan memperoleh hasil apa-apa karena prosesnya pun tidak pernah dilalui. Kalaupun ada, kemungkinannya adalah negatif: tidak pernah salah dan atau tidak pernah benar. Dari kemungkinan hasilnya saja, jelas bahwa orang yang berpikir lebih baik daripada orang yang tidak berpikir. Orang yang tidak berpikir tidak akan pernah mencapai kebenaran, sedangkan orang yang berpikir berpotensi menemukan kebenaran. Semakin keras berpikirnya, semakin tinggi tingkat kebenaran yang mungkin diraihnya.
Wahib memang sangat membenci orang yang tidak mau menggunakan pikirannya. Tulisan-tulisannya menganjurkan dan mendorong orang untuk berpikir sebebas-bebasnya tanpa dibatasi apa pun, kecuali aturan-aturan berpikir itu sendiri. “Saya kira orang yang tidak mau berpikir bebas itu menyia-nyiakan hadiah Allah yang begitu berharga yaitu otak. […] Mungkin akan ada orang yang mengemukakan bahaya dari berpikir bebas yaitu orang yang berpikir bebas itu cenderung atau bahkan bisa menjadi ateis. Betulkah? Orang yang sama sekali tidak berpikir juga bisa ateis! Lebih baik ateis karena berpikir bebas daripada ateis karena tidak berpikir sama sekali. Ya, meskipun sama-sama jelek.” (PPI, hal. 24)
Ya, ateis itu jelek. Karena itu jangan jadi ateis. Sampai di sini Wahib telah melalui tahap pertama cara bereksistensinya Kierkegaard, yaitu sikap estetis. Dengan berpikir bebas Wahib telah memeriksa pilihan-pilihan yang ada. Dari dua pilihan: Tuhan ada atau Tuhan tidak ada, Wahib jelas memilih yang pertama. Catatan-catatan hariannya secara keseluruhan menunjukkan betapa haus-rindunya Wahib akan Tuhan. Begitu intens pergulatan dan pencariannya hingga ia rela menempuh bahaya, tertatih-tatih dalam perjalanan panjang penuh rintang. Ia sangat menginginkan Tuhan hadir dan mempribadi dalam dirinya. Namun ia tak ingin sembarangan memilih Tuhan.
Dan kini ia bereksistensi ke tahap kedua, sikap etis. Nah, dari beragam agama dan kepercayaan yang menghidangkan bermacam Tuhan di dunia ini, Tuhan seperti apakah yang dipilih Wahib, yang ia dengan sukarela akan menyembahNya sepenuh hati?
Ahmad Wahib memang banyak memfokuskan pemikirannya pada masalah ketuhanan (teologi), sebab menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Fachry Ali (PPI, hal. 360), teologi memberikan integrasi dan sikap-sikap yang lebih riel dalam berbagai sektor kehidupan. Teologi adalah generalis yang paling tinggi dan meliputi. Namun sistem teologi paling mutakhir yang dipakai umat Islam selama ini adalah teologi produk abad ke-17, bahkan banyak yang masih memakai teologi produk abad-abad sebelumnya. Sistem teologi tersebut, dalam anggapan Wahib, tidak cukup memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan, tidak mampu lagi menumbuhkan dialog dan telah kehilangan daya gugahnya, karena sistem tersebut memakai bahasa yang tidak cocok lagi dengan bahasa abad sekarang.
Pemikiran Wahib belumlah merupakan sistem pemikiran yang selesai dan utuh, namun dari kumpulan catatannya yang tertinggal dapatlah penulis sarikan beberapa di antara konsepsi teologis yang hendak diajukannya:
Pertama, Tuhan Tidak Bisa Dibahasakan
Menarik di sini menyimak suatu ungkapan Wahib yang menyatakan bahwa “Allah dan wahyu-wahyuNya tidak bisa dilukiskan dengan sejuta macam kata-kata manusia dari bahasa apa pun juga. Allah dan wahyu jauh di atas potensi dan ekspresi akal dan budi manusia. Dia adalah ‘yang tak terucapkan’.” (PPI, hal. 132). Jadi sebelum bicara terlalu jauh, seolah-olah Wahib ingin mengatakan bahwa apa pun yang kita yakini tentang Tuhan, itu bukanlah Tuhan, melainkan hanyalah konsepsi dan keyakinan kita. Tuhan yang diuraikan berikut ini pun bukanlah Tuhan yang sebenarnya, melainkan hanya konsepsi dan keyakinan Ahmad Wahib. Tuhan yang sebenarnya bukan itu. Ia tak terucapkan. The Unutterable, bahasa Wittgenstein.
Namun, lanjut Wahib, meskipun Dia tersembunyi dari potensi dan ekspresi akal budi, “Dia selalu mendekati dan membimbing manusia sebagaimana manusia juga berusaha mendekati dan mencari hubunganNya. Dia menemui manusia dalam akal budi dan iman manusia, tapi Dia sendiri jauh lebih agung daripada akal budi dan iman itu sendiri. Dengan iman kita mencoba menerima Tuhan. Tapi Tuhan sendiri bukan iman. Iman sekedar medium pertemuan.” (PPI, hal. 132-133).
Kedua, Tuhan Bukan Daerah Terlarang bagi Pemikiran
Bagi Wahib Tuhan bebas untuk dipikirkan dan dianalisa sebagaimana halnya fenomena alam dan situsi sosial atau perkembangan politik. Pandangan ini bukannya tanpa bahaya. Akan tetapi hal ini merupakan konsekuensi logis dari pandangannya yang sangat mengagungkan pemikiran bebas. Dalam catatan berikut ini Wahib sekaligus menghantam pandangan yang anti-pemikiran bebas: “Sebagian orang meminta agar saya berpikir dalam batas-batas tawhid, sebagai konklusi global ajaran Islam. Aneh, mengapa berpikir hendak dibatasi? Apakah Tuhan itu takut terhadap rasio yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri? Saya percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran. Tuhan ada bukan untuk tidak dipikirkan ‘adanya’. Tuhan bersifat wujud bukan untuk kebal dari sorotan kritik. Sesungguhnya orang yang mengakui berTuhan, tetapi menolak berpikir bebas berarti menghina rasionalitas eksistensinya Tuhan. Jadi ia menghina Tuhan karena kepercayaannya hanya sekadar kepura-puraan yang tersembunyi.” (PPI, hal. 23).
Alangkah tajam serangan balik yang dilancarkan Wahib. Orang-orang yang tidak mau berpikir bebas dikatakan sebagai menghina Tuhan, kepercayaan mereka sebagai kepura-puraan yang tersembunyi. Dalam catatan lain, orang-orang seperti ini disebut Wahib sebagai munafik. Mereka tidak berani memikirkan sesuatu yang timbul dalam pikirannya, karena takut hal itu akan merusak keimanan, membuat Tuhan murka, dsb. Wahib mungkin berasumsi bahwa pikiran-pikiran tentang Tuhan, dari yang biasa saja sampai yang musykil, pasti ada pada setiap orang. Dan memang demikianlah adanya.
Anak kecil sering mempunyai gambaran yang aneh-aneh tentang Tuhan. Misalnya Tuhan itu seperti raksasa, berjubah hitam dan tinggal di puncak gunung; Tuhan itu seperti angin, bisa pergi ke mana suka; Tuhan putih seperti awan; Tuhan dapat menjewer telinga anak-anak yang nakal, Tuhan mempunyai mata yang melotot tajam menakutkan, dsb. Dan selalu khayalan aneh tentang Tuhan itu dibiarkan mengalir dalam kesadaran, bahkan diucapkan dan diperbincangkan bersama teman-teman sebagai tema yang mengasikkan, sampai suatu saat orang tua atau guru membentak dan mengatakan: tidak boleh.
Menginjak dewasa, seiring kemajuan tingkat berpikir, bayangan-bayangan yang bersifat konkret itu memang menghilang, tetapi pikiran-pikiran aneh tentang Tuhan sebetulnya tetap ada, berganti menjadi pikiran yang lebih abstrak. Namun bersamaan dengan itu, kesadaran pun tertutup oleh tabu-tabu dan larangan sehingga orang menjadi takut akan pikirannya sendiri dan lalu berusaha menguburnya ke bawah sadar. Sigmund Freud menggolongkan gejala ini sebagai salah satu mekanisme pertahanan ego yang disebut represi. Tentang orang-orang seperti ini Wahib mengadu kepada Tuhan: “Aku percaya bahwa Engkau tidak hanya benci kepada ucapan-ucapan yang munafik, tapi juga benci pada pikiran-pikiran yang munafik, yaitu pikiran-pikiran yang tidak berani memikirkan yang timbul dalam pikirannya, atau pikiran yang pura-pura tidak tahu akan pikirannya sendiri.” (PPI, hal. 31).
Wahib yakin bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah membatasi pikiran manusia, termasuk untuk memikirkan diriNya. Apa untungnya pembatasan itu bagi Tuhan, dan apa pula yang mesti dikhawatirkan. Toh pikiran itu Ia yang menciptakan, mekanisme dan kemampuannya Ia yang atur, dan setinggi-tingginya kapasitas barang ciptaan, tidak akan menyamai apalagi melebihi kapasitas yang menciptakannya. Justru Tuhan memberikan pikiran kepada manusia agar digunakan sebaik-baiknya, sebebas-bebasnya, sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin, sampai pada batas yang paling jauh. Kata Wahib: “…sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa Tuhan itu tidak membatasi, dan Tuhan akan bangga dengan otak saya yang selalu bertanya, tentang Dia.” (PPI, hal. 23). Ketakutan berpikir bebas tentang Tuhan akan membuat pemahaman tentang Tuhan menjadi beku. Padahal Tuhan itu hidup, segar, dan tidak mau dibekukan.
Menurut Wahib, pemikiran bebas akan menghasilkan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang Tuhan, pengertian yang murni, ketersingkapan, tanpa diselubungi kepalsuan-kepalsuan dan keterpaksaan-keterpaksaan yang tidak disadari. “Apakah aqidah itu melarang adanya suatu pertanyaan dalam akal yang meragukan sebagian dari isi aqidah itu? […] Menurut saya aqidah itu demokratis, yaitu aqidah mencintai sekaligus juga menghargai “anti-aqidah”, walaupun aqidah tidak menyetujui isinya. Hanya dengan demikian orang akan sampai pada aqidah yang sebenar-benarnya dan bukan ‘pseudo-aqidah’ atau ‘aqidah slogan’.” (PPI, hal. 47). Inilah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan.
Akal tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Justru itulah alat yang diberikan Tuhan agar manusia bisa bereksistensi di dunia. Untuk bisa bereksistensi, akal manusia harus diberi kemerdekaan penuh, sebab hanya pada kemerdekaanlah kemampuan memilih dan bertanggung jawab bisa berperan. Oleh karena itu membatasi akal hanyalah merupakan usaha yang sia-sia, bahkan salah besar karena dapat menurunkan harkat dan derajat manusia. “Meninggalkan akal bisa,” tulis Wahib. “Tapi ini pun memakai akal. Menggunakan akal untuk meninggalkan akal. Menggunakan akal dalam meninggalkan objektivitas menuju subjektivitas untuk sampai kepada kebenaran.” (PPI, hal. 48). Akal adalah sarana menuju kebenaran.
Meskipun menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap akal, Wahib tidak menempatkan akal manusia pada posisi absolut. Ia mengakui bahwa akal itu relatif dan berbatas. “Tapi siapa yang tahu batasnya itu? Otak atau pikiran sendiri tidak bisa menentukan sebelumnya. Batas kekuatan itu akan diketahui manakala otak kita sudah sampai di sana dan percobaan-percobaan untuk menembusnya selalu gagal. Karena itu manakala “keterbatasan kekuatan berpikir”, maka jelas statement ini tidak berarti dan mungkin salah besar. Otak itu akan melampaui batas kekuatannya.” (PPI, hal. 24-25). Lagi pula akal itu bermacam-macam, sejumlah banyaknya manusia yang mempunyai otak. Akal manusia yang satu bisa dikelabui atau dipengaruhi oleh akal manusia lain yang mampu berpikir lebih kuat. Oleh karena itu Wahib tidak menempatkan akal sebagai sumber ajaran Islam. Tidak proporsional, katanya. Sumber Islam itu hanya dua, yaitu al-Quran dan as-sunnah. Akal hanyalah sebagai alat untuk menggali kedua sumber tersebut (PPI, hal. 20). Pemikiran ini tampak sangat ortodoks terutama jika menilik Wahib adalah seorang yang sangat liberal. Penentuan sumber Islam yang dipakainya ini berbeda jauh dengan, sebutlah misalnya tokoh JIL (Jaringan Islam Liberal) Ulil Abshar Abdalla, yang secara ekstrim menyebutkan bahwa akal adalah sumber pertama ajaran Islam, di atas al-Quran dan as-sunnah (tradisi).
Ketiga, Tuhan yang Lain
Wahib menginginkan Tuhan yang lain, yang berbeda dengan yang dipahami kebanyakan orang. Menurutnya Tuhan yang dipahami sekarang ini tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya. Yang diinginkannya adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Tuhan yang besar, agung, kuasa, dsb, karena Ia memang benar-benar besar, agung, kuasa. Tuhan yang Ada karena Ia memang Ada. Ada pada dirinya sendiri. Das Ding an Sich, meminjam secara kurang tepat istilah Kant. Tuhan adalah X karena Ia memang X, bukan karena faktor lain. Ia menulis: “Adakah Tuhan besar karena manusia merasa kecil di hadapan ombak yang gemuruh bergelora? Adakah Tuhan agung karena manusia merasa tidak berdaya di hadapan alam yang luas, laut yang tiada bertepi? Kalau begitu Tuhan besar karena kekecilan manusia. Alangkah sederhananya ketuhanan yang demikian. Aku tak mau Tuhan seperti itu! Bagiku Tuhan tidak kontradiksi dengan manusia. Aku mencari tuhan yang lain.” (PPI, hal. 139).
Meskipun kadangkala Wahib meragukan Tuhan, sesungguhnya hal itu dilakukan untuk lebih menguatkan iman kepadaNya. Kebebasan berpikirnya sama sekali tak dimaksudkan untuk menolak Tuhan. Aku mencari Tuhan yang lain! Namun Tuhan yang lain itu sebetulnya adalah Tuhan yang “itu-itu” juga, Tuhan yang kepadaNya ia akan pasrah sepenuhnya menyerahkan seluruh jiwa-raga. Ia memang mengritik banyak pandangan yang menurutnya justru merendahkan Tuhan, dan ia ingin membersihkan Tuhan dari pandangan-pandangan yang demikian.
Wahib ingin mengetahui Tuhan menurut Tuhan itu sendiri.
Namun “kelainan-kelainan” Tuhan itu pun sebetulnya masih bisa diidentifikasi sebagai berikut. Tapi ingat konsep pertama, bahwa Tuhan tidak bisa dibahasakan. Jadi walaupun saya menyebut beberapa sifat Tuhan di sini, sebetulnya itu bukanlah Tuhan itu sendiri.
Keempat, Tuhan Demokratis
Tuhan demokratis berarti Tuhan yang mau mendengar kata-kata hambaNya, Tuhan yang bisa diajak berdebat, Tuhan yang tidak otoriter dalam menetapkan suatu hukum, tetapi juga memperhatikan keberatan-keberatan hamba-hamba yang dikenai hukum tersebut. Wahib berdoa: “Tuhan, bisakah aku menerima hukum-hukummu tanpa meragukannya terlebih dahulu? Karena itu Tuhan, maklumilah lebih dulu bila aku masih ragu akan kebenaran hukum-hukumMu. Kalau Engkau tak suka hal ini, berilah aku pengertian-pengertian sehingga keraguan itu hilang dan cepat-cepatlah aku dibawa dari tahap keragu-raguan kepada tahap penerimaan.” (PPI, hal. 30).
Demokratis berarti tidak egois, tidak merasa benar dan ingin menang sendiri. “Andaikata Tuhan sendiri berpendapat bahwa inti Islam itu tawhid, apakah itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu egoistis?” (PPI, hal. 100). Tuhan demokratis berarti juga Tuhan yang memandang memandang manusia (makhlukNya) sederajat satu sama lain. Tidak mendiskriminasikan manusia berdasarkan ras, bangsa, suku, golongan, bahkan agama. Tentang yang terakhir ini Wahib memang awalnya tampak masih ragu-ragu. Ungkapannya disampaikan dalam nada bertanya: “Aku tak tahu, apakah Tuhan sampai hati memasukkan dua orang bapakku (pendeta Kristen -pen.) itu ke dalam api neraka. Semoga tidak.” (PPI, hal. 41). Pemikiran liberal Islam yang berkembang sekarang sudah lebih tegas dalam masalah ini, bahwa keselamatan eskatologis bukan hanya ada dalam Islam. Asalkan dia beriman, percaya kepada hari kemudian, dan berbuat baik kepada sesama makhluk (beramal saleh) [lihat surat al-Baqarah (2) ayat 62], Tuhan pasti memasukkannya ke dalam surga.
Dalam catatan lainnya Wahib lebih tegas: “Nah, andaikata hanya tangan kiri Muhammad yang memegang kitab, yaitu al-Hadits, sedang dalam tangan kanannya tidak ada wahyu Allah (Al-Quran), maka dengan tegas aku akan berkata bahwa Karl Marx dan Frederik Engels lebih hebat dari utusan Tuhan itu. Otak kedua orang itu yang luar biasa dan pengabdiannya yang luar biasa pula, akan meyakinkan setiap orang bahwa kedua orang besar itu adalah penghuni sorga tingkat pertama, berkumpul dengan para nabi dan syuhada.” (PPI, hal. 98). Dengan demikian, postulat dalam NDP HMI yang menyatakan bahwa di antara sekian banyak kepercayaan, hanya satu yang benar atau salah semuanya, menjadi tergoyahkan. Penulis tidak tahu persis bagaimana pandangan Cak Nur, yang memasukkan postulat itu ke dalam NDP, tentang hal tersebut saat ini, sebab saat menulis itu Cak Nur masih seorang Natsir Muda.
Kelima, Tuhan Penuh Cinta
Tuhan yang dirindukan Wahib adalah Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh pengertian, penuh perhatian, tidak suka mengancam dan menakut-nakuti, serta tidak suka marah kepada hamba-hambaNya. Pada Tuhan semacam itulah Wahib akan menjatuhkan sembah dan cintanya, mengingatNya penuh seluruh. Coba rasakanlah getar kerinduan nan mesra pada doa Wahib berikut ini: “Tuhan, aku menghadap padaMu bukan hanya di saat aku cinta padaMu, tetapi juga di saat-saat aku tidak cinta dan tidak mengerti tentang diriMu, di saat aku seolah-olah memberontak terhadap kekuasaanMu. Dengan demikian, Rabbi, aku mengharap cintaku padaMu akan pulih kembali. Aku tidak bisa menunggu cinta untuk sebuah sholat.” (PPI, hal. 27).
Pada Tuhan yang penuh cinta itu pula Wahib sering memanjatkan doa-doanya yang tulus, untuk kemudahan urusannya, ketentraman jiwanya, keselamatan keluarganya, kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya, dan untuk kebaikan seluruh manusia pada umumnya.
Keenam, Tuhan menurut Islam
Agama yang dipilih Wahib adalah Islam. Maka konsepsi-konsepsi tentang Tuhan yang ia anut adalah yang berdasarkan sumber-sumber Islam (Quran dan hadits) sebagaimana ia pahami. Wahib meyakini, misalnya sebagaimana disebutkan dalam al-Quran [QS. Al-Ikhlash (112): 1-4], bahwa Tuhan itu Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Wahib telah bergaul dengan para penganut banyak agama, dan pasti telah belajar pula sistem teologi mereka. Pemilihannya pada Islam sebagai agama tentulah karena, di antaranya, dilandasi keyakinan rasional bahwa sistem teologi dalam Islam adalah yang paling baik dan sempurna, paling sesuai dengan level abad modern. Ia memang masih bertanya: “Apakah gambaran Tuhan dalam Quran itu cukup potensial diinterpretasi bagi level Arab abad ketujuh ke atas?” (PPI, hal. 118). Namun tentu saja Wahib takkan menemukan agama lain yang lebih modern daripada Islam. Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, dsb. lebih kuno daripada Islam. Komunisme dan sosialisme memang lebih modern, tapi keduanya bukan agama, dan pula cenderung ateis.
Namun konsep sumber-sumber Islam tentang Tuhan itu tidaklah lantas membatasi kreativitasnya untuk terus menggali dan mempertanyakan konsep-konsep yang ada. Kalau perlu ia akan menyusun konsep ketuhanan yang lain, yang lebih sesuai dengan pendapatnya. Konsep Islam yang dirasanya tidak rasional kalau perlu tidak usah diterima. “Kadang-kadang hatiku berpendapat bahwa dalam beberapa hal ajaran Islam itu jelek. Jadi ajaran Allah itu dalam beberapa bagian jelek dan beberapa ajaran manusia, yaitu manusia-manusia besar, jauh lebih baik.” (PPI, hal. 21). Begitulah jika pemikiran bebas dibiarkan bicara. Tetapi Wahib sama sekali tidak bermaksud menolak Islam. Ia hanya ingin mendapatkan kebenaran Islam yang lebih hakiki, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. “Bagaimana kita bisa yakin bahwa seluruh ajaran Islam benar kalau kemungkinan adanya kelemahan pada ajaran Islam tidak pernah terlintas di pikiran untuk selanjutnya dipikirkan kemungkinan benarnya.” (PPI, hal. 47).
Sekali lagi tentang keharusan berpikir bebas, Wahib memutuskan “Kalau betul Islam itu membatasi kebebasan berpikir, sebaiknyalah saya berpikir lagi tentang anutan saya terhadap Islam ini. Maka hanya ada dua alternatif yaitu menjadi muslim sebagian atau setengah-setengah atau malah menjadi kafir.” (PPI, hal. 23). Sebuah keputusan yang menujukkan betapa teguhnya Wahib memegang prinsip. Ia rela meninggalkan Islam jika agama tersebut membatasi kebebasan berpikir. Ia akan mencari Islam yang lain. Islam menurut Tuhan, atau Islam yang menurut hati nuraninya benar-benar merupakan pendapat Tuhan.
Pada intinya, Tuhan yang lain yang dicari Wahib tetaplah Tuhan yang Islam. Ia ingin sungguh-sungguh menjadi muslim secara total, kaffah, dengan mengakui dan mengabdikan diri kepada Tuhan yang Islam itu. Ia mengakui bahwa pada resultante terakhir, Islam itu secara total baik dan sempurna. “Akalku sendirilah yang tidak mampu meraba kesempurnaan tadi,” tulisnya. (PPI, hal. 21). Jelas sekarang, Wahib telah menukik semakin dalam, memasuki tahap ketiga cara bereksistensi: sikap religius. Wahib telah seutuhnya menjadi homo religius.
Karena itu barang siapa yang meragukan keislaman Wahib, sungguh dia tidak mengerti akan Wahib. Membaca Wahib harus dilakukan secara keseluruhan. Bukan hanya pada hasil pemikiran tetapi juga pada prosesnya. Selain itu ia harus berlaku arif dalam memahami gejolak psikologis anak muda. Wahib adalah seorang yang sedang dan telah mencoba menjalani hidup seperti seorang filsuf. Kasihan sekali ia, sebab menurutnya “filsuf adalah orang yang senantiasa berada dalam krisis. Dan demi kesejahteraan dunia, tidak perlu semua orang tenggelam dalam krisis yang abadi.” (PPI, hal. 56). Betul. Tidak perlu semua orang menjadi Wahib. Dan syukurnya di dunia ini orang-orang yang seperti Wahib hanya segelintir. Namun lucunya, pada saat yang sama Wahib pun ingin hidup sebagai seorang muslim. “Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan budha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim.” (PPI, hal. 46). Dua predikat yang kontradiktif dan tidak mungkin disatukan, sebagaimana dikatakannya sendiri “filsuf itu tidak perlu dan tidak boleh beragama. Begitu dia beragama, begitu dia berhenti jadi filsuf.” (PPI, hal. 56).
Karena itu, jika kita tak pernah mencela Ibrahim saat ia jadi penyembah bulan dan matahari, kenapa kepada Wahib kita mesti menunjukkan antipati? Kita harus adil, kata Jean Marais kepada Minke, sejak dalam pikiran.
Wallahu a’lam [Asso].
Catatan:
Esai ini menjadi satu dari lima nominator Ahmad Wahib Award 2003 yang diselenggarakan oleh Freedom Institute dan HMI Cabang Ciputat.